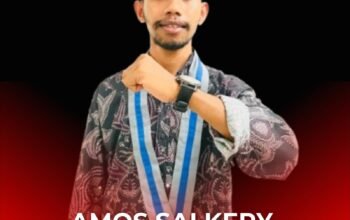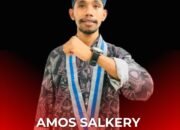DETIK SUMBA – Di tengah zaman yang katanya merdeka ini, kita masih harus bertanya: bagaimana mungkin sebuah negeri yang katanya demokratis malah makin sulit dibedakan dari barak militer? Injil menenangkan kita dengan janji: “Mintalah, maka kamu akan diberi; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” Tapi mungkin yang belum dijelaskan adalah: pintu itu akan dibukakan oleh siapa? Apakah oleh rakyat, atau oleh mereka yang berdiri tegap sambil membawa pangkat di balik jas sipil?
Kita hidup di negeri yang penuh permohonan, tapi minim keberanian. Karena itu Yakobus mengingatkan kita: “Siapa tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa.” Sayangnya, hari-hari ini, kita terlalu sering tahu tapi pura-pura bodoh. Terlalu paham tapi memilih diam. Terlalu beriman, sampai-sampai menyerahkan semua urusan bangsa pada Tuhan dan pada jenderal.
Bangsa ini, entah dengan sadar atau setengah mengantuk, sedang membiarkan seragam masuk ke ruang yang dulu diperjuangkan oleh darah rakyat biasa. Dari kementerian hingga kursi kepala daerah, dari BUMN sampai ke lembaga-lembaga yang seharusnya netral semuanya kini tampak seperti perpanjangan dari komando. Data menunjukkan peningkatan signifikan penempatan purnawirawan militer atau perwira aktif di posisi-posisi strategis sipil, dari komisaris BUMN hingga jabatan direktur di berbagai kementerian, bahkan staf khusus. Fenomena ini, yang sering kali disebut “militerisasi sipil” atau “dwifungsi gaya baru”, menimbulkan kekhawatiran serius tentang erosi prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.
Padahal Bung Karno sudah pernah berteriak, dengan suara serak tapi tegas: “Tentara adalah alat negara, bukan alat partai, bukan alat golongan, dan tidak boleh jadi alat kekuasaan sipil untuk menindas rakyatnya sendiri.” Tapi rupanya teriakan Bung Karno kini cuma jadi kutipan di buku pelajaran yang tak pernah dibaca. Marhaenisme, warisan ideologisnya, kini mungkin hanya tinggal nama: ditempel di baliho, dijual dalam seminar, tapi dilupakan dalam kebijakan.
Sementara rakyat kaum marhaen sejati masih tetap mengantre minyak goreng, membayar pajak sambil menunduk, dan melihat anak-anaknya tumbuh di negeri yang makin rapi secara protokol tapi makin rusak secara keadilan. Harga-harga kebutuhan pokok terus bergejolak, upah riil stagnan, sementara ruang partisipasi publik kian menyempit. Undang-undang seperti UU ITE dan revisi KUHP semakin sering digunakan untuk membungkam kritik, menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat sipil. Data menunjukkan peningkatan laporan kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang menyuarakan ketidakpuasan. Ini adalah kontradiksi ironis di negeri yang mengklaim sebagai surga demokrasi.
Apakah ini reformasi? Atau restorasi barak? Apakah kita sedang memperkuat negara? Atau sekadar menambal lubang demokrasi dengan bendera, senjata, dan simbol-simbol gagah?
Dan lucunya, semua ini dibungkus dengan jargon: “demi stabilitas.” Seolah-olah rakyat adalah ancaman. Seolah-olah sipil tidak mampu mengurus negaranya sendiri tanpa dituntun oleh tangan bersarung militer. Narasi stabilitas ini seringkali menjadi justifikasi untuk menekan perbedaan pendapat dan memusatkan kekuasaan.
Proyek-proyek pembangunan skala besar yang sarat dengan intervensi militer, pengamanan demonstrasi yang berlebihan, dan respons terhadap isu-isu sosial yang mengedepankan pendekatan keamanan, adalah bukti nyata bagaimana “stabilitas” diterjemahkan dalam praktik. Padahal, stabilitas sejati dalam demokrasi lahir dari keadilan, partisipasi, dan kepercayaan rakyat, bukan dari ketakutan atau hegemoni militer.
Kini marhaenisme tak lagi bermakna keberpihakan pada rakyat kecil, tapi jadi alat politik untuk menjustifikasi kekuasaan yang tak pernah puas. Dan agama? Kadang dipinjam juga. Doa-doa dipanjatkan di podium, tapi lupa bahwa iman sejati bukan sekadar minta berkat, melainkan berani berdiri di pihak yang benar meski sendiri. Penggunaan simbol dan retorika agama untuk kepentingan politik praktis, terutama dalam konteks elektoral, juga semakin masif. Ini mengaburkan batas antara ranah spiritual dan kepentingan kekuasaan, seringkali memecah belah masyarakat dan mengikis nilai-nilai kebhinekaan.
Karena jika kita tahu ini salah dan kita tetap diam, maka kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah bagian dari dosa itu sendiri. Sebab demokrasi bukan soal siapa yang paling tegap berdiri, tapi siapa yang paling jujur mendengar. Dan negara bukanlah panggung untuk pamer pangkat, tapi ladang untuk merawat keadilan.
Maka hari ini, mari kita berhenti pura-pura buta. Pintu langit memang harus kita ketuk tapi jangan lupa, pintu keadilan di bumi pun harus kita dobrak jika terlalu lama dibiarkan terkunci oleh tangan-tangan yang tak seharusnya memegang kunci.
Karena negeri ini, sekali lagi, bukan milik jenderal, bukan milik elite, apalagi milik mereka yang takut kehilangan kuasa tapi milik marhaen yang masih percaya bahwa kejujuran, keberanian, dan kebaikan adalah senjata yang lebih kuat dari senapan.***
| Ikuti Berita Terbaru Kami di Detik Sumba dengan KLIK DI SINI. |